 |
| Bukti chat kritik yang akhirnya berbuah dikick oleh admin Komunitas Pena Karya (Kopek) bernama Titik Sari. Foto: dokumen pribadi. |
Oleh M. Abdullah Badri
MENURUT saya, menulis memiliki tiga keuntungan. Yakni 1). Ilmu, 2). Popularitas, dan 3). Royalti atau uang.
Penulis pasti kaya ilmu. Alasannya, untuk mendapatkan karya tulis, penulis harus memiliki masalah. Tanpa masalah, tiada karya. Untuk itu, penulis yang belum memiliki masalah yang ditulis, dia sering mencari masalah dengan cara membaca buku, berdiskusi, berkumpul dengan sesama penulis kreatif agar mendapatkan ide masalah, untuk kemudian solusinya ditulis, entah dalam bentuk artikel, esai, cerpen, puisi, berita atau narasi lain.
Penulis yang malas membaca sering mengalami stag ide dan gagasan. Kosakatanya pun terbatas. Tidak tandas dan lugas dalam menulis dan cenderung bertele-tele serta tidak populis, membosankan. Logika penulis malas tidak memperkaya gagasan pembaca, yang butuh asupan gizi pengetahuan baru.
Tulisan yang tidak disebar -seperti skripsi yang mangkrak di perpus kampus itu-, manfaatnya tidak dirasakan oleh pembaca luas. Pengetahuan dan gagasan dalam tulisan itu akhirnya hanya menjadi anak gagasan penulis yang tidak berkembang dinikmati publik.
Oleh karena itulah, tulisan yang baik ialah tulisan yang bisa menarik orang lain membaca sejak dari paras judulnya, body menarik kontennya hingga ekor epilognya. Di sini, media berperan penting sebagai jembatan penulis mendapatkan pengaruh, popularitas serta nama besar (bila diakui oleh publik).
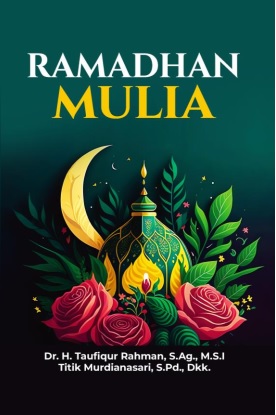 |
| Cover buku terbitan Kopek yang memuat tulisan saya. |
Barangkali, sebuah kitab, buku, artikel, sudah ditinggal mati oleh penulisnya. Namun, karena tulisannya masih menarik dan dibutuhkan oleh anak zaman setelah eranya, nama penulis masih terdengung manis berabad-abad. Menulis karya bagian dari menaikkan citra dan popularitas. Memang, tidak semua sesuatu yang besar dimulai dari menulis. Tapi, dari menulis, banyak sesuatu yang besar, bisa dimulai.
Bila buku hanya dicetak 25 eks per judulnya, matematika popularitas gagasan penulis sulit diwujudkan. Sekarang ini, di zaman digital ini, penulis lebih mudah mendapatkan popularitasnya dari media sosial. Tradisi menulis dalam bentuk cetak mulai terkurung hanya sebatas baro'ah dzimmah (menyelesaikan tuntutan) profesi seperti kredit poin, syarat lulus, syarat seleksi dan semacamnya.
Kualitas buku pun akhirnya makin terjun ke jurang pengetahuan yang miskin gagasan. Diakui atau tidak, buku yang terbit karena tuntutan profesi akan berakhir seperti maqbaroh ribuan naskah skripsi di perpustakaan kampus. Publik luas tidak mengaksesnya.
Akhirnya, janji bahwa menulis akan menghasilkan royalti pun sulit diwujudkan. Bagaimana bisa seorang penulis akan mendapatkan royalti bila buku yang dicetak hanya 25 eksemplar, dan keuntungannya hanya 5 persen dari, misalnya, Rp. 5.000 harga jual?
 |
| Bukti chat dari admin Kopek. |
Misal laku 20 eksemplar pun, penulis baru mendapatkan keuntungan Rp. 50.000. Itu pun kalau bukunya dianggap menarik oleh calon pembeli. Kalau tidak, ya wassalam. Royalti tidak sebanding dengan proses menulis, yang butuh membaca semalaman, menulis berjam-jam, berikut gorengan, rokok, dan waktu yang dihabiskan di depan komputer.
Bagi penulis yang memiliki misi baro'ah dzimmah, mereka rela membayar agar tulisannya dimuat oleh media, seperti era digital sekarang. Di zaman saya kuliah dulu, menulis bisa menjadi penopang biaya kuliah bertahun-tahun. Sekarang? Tidak. Banyak media cetak yang sekarang tidak mau membayar penulis karena era cetak makin hilang ditelan digital massa tak terbendung.
Kini, tulisan media cetak pun banyak dihiasi oleh para penulis yang mau membayar untuk baro'ah dzimmah. Demikian pula media online dan penerbit buku-buku indie. Tidak banyak penulis kreatif yang menaruh percaya kepada penerbit. Tengok misalnya, penulis Novel Suhita lebih tertarik mencetak sendiri dan menjualnya sendiri dengan sistem yang dia buat sendiri daripada harus melalui penerbit, yang lebih mengutamakan profit awal (dibayar).
Sangat memprihatinkan bila ada komunitas penulis mengundang penulis di luar komunitasnya agar mau berkarya untuk dijadikan buku antologi, tapi hanya dicetak 25 eksemplar. Dan masing-masing penulis diwajibkan untuk membeli bila ingin membaca tulisannya sendiri dalam buku tersebut. Bila ingin mendapatkan keuntungan, harus jual sendiri, berkeringat sendiri. Repot.
Cetakannya saja hanya 25 eksemplar. Berarti, bila salah satu penulis berhasil menjual sold out jumlah cetakan awalnya, dia hanya akan mendapatakan keuntungan yang tidak layak.
Siapa yang paling diuntungkan di sini? Hanya ada satu kelompok. Yakni, yang menulis untuk meringankan beban taklif profesinya (baro'ah dzimmah). Yang lain harus ikhlash menjadi "sapi perah". Selamat buat Komunitas Pena Karya dan para penulis yang butuh kredit poin! Tanpa seleksi, karya tetap tayang. Sekali lagi, selamat! [badriologi.com]






